INIKAH WAJAH DEMOKRASI KITA?

Kematian Ketua DPRD Sumatra Utara Abdul Azis Angkat di tengah riuh rendahnya demonstrasi menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli adalah sesuatu yang bermakna tunggal: Anarkisme kini kembali berkuasa dan dipilih sebagian masyarakat negeri ini untuk mewujudkan keinginannya.
Ada yang tumpang tindih di sini, mengapa untuk membentuk daerah administrasi baru atau memekarkan provinsi induk, jalan tak beradab yang dipilih? Demokrasi memiliki prosedur, dan tatkala prosedur memperoleh persetujuan parlemen daerah belum dikantongi, apakah jalan kekerasan menjadi absah?
Politik pemekaran hakikatnya berwajah rangkap, sebagian digerakkan untuk memajukan aspirasi masyarakat setempat. Dalam konteks ini, masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan dan Samosir. Tapi, sebagian lagi berdiri diatas klaim—untuk tak mengatakan politisasi elite-elite lokal.
Dalam perjalanan otonomi daerah yang berderu sejak 1999 silam, boleh dibilang ide memekarkan daerah (provinsi, kabupaten/kota) lebih banyak berawal dari elite lokal dan bukan murni kebutuhan masyarakat setempat. Klaim dalam model pemekaran demikian, tak lain kepanjangan tangan hasrat berkuasa dari elite lokal atau politisi yang menumpang di balik ide suci mengembangkan atau memajukan daerah.
Penyebab kematian Abdul Azis Angkat masih diselidiki. Bisa jadi ia meninggal karena faktor penyakit yang diidapnya. Namun politisi Partai Golkar ini tak pantas mendapat perlakuan kasar: ditendang, dipukul dan dianiaya kendatipun misalnya ia menolak atau merintangi usul pembentukan Provinsi Tapanuli. Bukankah musuh utama demokrasi—jika betul sistem ini yang ingin dihidupkan di negeri ini—adalah anarkisme? Kekerasan sesungguhnya merupakan jalan lain untuk mengubur demokrasi.
Marilah kita mengingat Plato dan Aristoteles, dua filsuf yang hidup di Yunani ribuan tahun lalu. Keduanya tak terlalu memfavoritkan sistem pemerintahan dan sistem politik demokrasi yang kini paling banyak dianut banyak negeri di planet bumi ini. Sistem demokrasi kadang kala tak bisa menjaring para demagog, penumpang gelap atau penjahat yang hakikatnya hendak membajak sistem ini. Maka kerap kali ada demokrasi tanpa kaum demokrat. Sering pula kaum demokrat justru hidup dalam otoritarianisme.
Tak pelak keduanya menawarkan monarki atau aristokrasi walaupun sama-sama memiliki celah atau lubang. Dua sistem ini tak bisa menjamin bahwa pemimpin atau penguasanya tidak korup dan amanat. Sistem monarki dipimpin seorang penguasa yang adil, bijaksana dan selalu mendengar aspirasi rakyat. Sedangkan aristokrasi dipimpin sekelompok kecil orang yang terdiri atas kaum cerdik pandai yang bijaksana, jujur, dan aspiratif.
Yang ingin disampaikan bijak bestari ini, sistem politik termasuk demokrasi hanyalah cara dan bukan tujuan itu sendiri. Dan karena demokrasi memberikan kemungkinan lebih luas kepada setiap rakyat (demos), maka sistem ini dianggap lebih rasional dan sesuai kebutuhan zaman. Tapi satu lagi harus menjadi batu bata. Seperti disitir Nurcholish Madjid (Cak Nur), demokrasi harus berlandaskan keadaban (civility). Dan ini menyaratkan budaya yang senafas dengan sistem demokrasi. Susahnya, ini yang mencemaskan, masyarakat di barisan zamrud khatulistiwa ini kurang (atau tak!) memiliki budaya demikian.
Tengoklah fakta. Di Maluku Utara, pilkada harus mengambil jalan berkelok untuk mendapatkan siapa pemenangnya. Aksi massa menjadi pemandangan umum untuk bernegosiasi. Demokrasi telah menjerat warga di sana berhadapan satu sama lain. Konflik horizontal tak terbendung. Di Nusantara ini, majoritas warganya hanya sanggup menang dan belum siap kalah. Maka, kita ketinggalan jauh dengan Amerika Serikat. Di sana, yang kalah menyampaikan selamat kepada pemenang tanpa merasa kehilangan muka. Satu lagi, mereka menjunjung tinggi hukum dan menjadikannya sebagai acuan bersama.
Negeri ini pun menyebut negara hukum. Alamak…kesetiaan terhadap hukum masih saja jauh panggang dari api. Keputusan Mahkamah Konstitusi disebut bersifat final dan mengikat. Terkait pilkada Jawa Timur, MK memutuskan agar dilakukan pencoblosan ulang dan penghitungan ulang di tiga kabupaten di Madura. Putusan ini sudah dilaksanakan KPU Jatim, KPU Pamekasan, KPU Bangkalan dan KPU Sampang. Hasil penghitungan suara pun telah diumumkan. Tapi tetap saja, keputusan ini digugat. MK “diinterupsi” seolah keputusannya tak lagi bersifat final dan mengikat. Maka benarlah sindirin kaum sinis, demokrasi kita baru di permukaan alias demokrasi prosedural!
Kembali ke pemekaran. Agaknya bijaksana jika segenap bangsa ini merenungi ide yang tampak elok di permukaan, tapi menyimpan bara api tersebut. Dari 1999 hingga Agustus 2008, telah terbentuk 191 daerah otonom baru yang terdiri atas 7 provinsi, 153 kabupaten dan 31 kota. Itu berarti ada 510 daerah otonom, yang terdiri atas 33 provinsi, 386 kabupaten dan 91 kota. Laju pemekaran daerah tak pelak sungguh deras. Benarkah semua itu didasari semangat untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah serta meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum?
Apa tidak relevan untuk memikirkan kembali moratorium. Bias. Itulah yang seyogianya dihindari. Dan karena setahun ini negeri kita akan menghelat pemilihan umum, adalah bijaksana jika setiap rencana pemekaran ditangguhkan dulu. Lebih baik menyisingkan lengan baju untuk membuktikan bahwa sebagai warga bangsa, kita memiliki budaya yang setangkup dengan demokrasi. Setelah itu baru kembali memikirkan urusan lokal. Kita ingin apa yang menimpa Abdul Azis Angkat menjadi monumen terakhir, situs untuk melihat “sisi gelap” demokrasi tanah air. 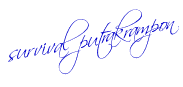

.jpg)

0 comments:
Post a Comment